Hal ini seakan menjadi potret bagi kaum millenials, generasi yang lahir dibentuk pada saat perubahan mode ekonomi sejalan dengan perubahan teknologi, masyarakat dan sistem pendidikan (Kelan & Lehnert, 2009).
Perubahan gaya hidup dan kehidupan sosial yang dialami oleh kaum milenial sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berupa media sosial (Zhang et al., 2011 dan Wang et al., 2011). Adanya media sosial membuat para milenial ingin selalu mengaktualisasi diri dengan selalu mengikuti tren yang berlaku di masyarakat.
Dalam sebuah artikel yang dirilis oleh Buzzfeed berjudul “The Urban Poor You Haven’t Noticed: Millenials Who’re Broke, Hungry, but on Trend”, memberikan gambaran bahwa kaum milenial yang baru bekerja banyak menghabiskan gajinya untuk tampil ‘kekinian’. Meningkatnya transaksi cashless dan produk fintech, juga berperan membuat milenial menjadi lebih mudah untuk membelanjakan uangnya karena tidak merasa mengeluarkan uang secara fisik. Pada akibatnya, kaum milenial menjadi kaum urban yang hedonis dan semakin konsumtif.
Tidak hanya menabung, kaum milenial juga luput dalam hal investasi, baik investasi aset, pasar modal, ataupun dana pensiun. Hal ini diperkuat dengan data OJK (2015), terdapat penurunan rasio Marginal Propensity to Save (MPS) dan meningkatnya rasio Marginal Propensity to Consume (MPC). Rendahnya MPC dibandingkan dengan MPS menjadi indikasi bahwa terdapat shifting perilaku masyarakat yang lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk kegiatan belanja dibandingkan dengan untuk menabung maupun berinvestasi.
Dalam jangka panjang dan dipandang dari segi makroekonomi, penurunan rasio MPS akan berpengaruh pada ketersediaan dana yang semakin berkurang dan membuat Indonesia harus tetap mengandalkan pembiayaan dari sumber hutang luar negeri.
Adanya konsep sharing economy yang seolah melekat dalam kehidupan kaum milenial menjadi salah satu utama mengapa kaum milenial cenderung tidak memiliki aset. Hal ini bisa dilihat dari berkembangnya bisnis berbasis sharing dan mengandalkan teknologi, misalnya penginapan airBnB, Uber, Go-Jek, Co-Working Space dan lain sebagainya.
Akibatnya, banyak milenial yang cenderung memilih menyewa apartemen dibanding memilikinya ataupun banyak milenial yang saat ini memilih menggunakan transportasi online dibandingkan membeli kendaraan.
Dari sudut pandang pasar modal, penelitian di Amerika menyatakan bahwa hanya 23,8% yang memiliki saham atau mutual funds. Alasan rendahnya tingkat kepemilikan saham, selain karena budaya milenial yang cenderung boros, tetapi juga karena meskipun terdapat perkembangan teknologi membuat banyaknya penciptaan produk dan jasa finansial yang baru, namun, perlu diingat bahwa dari beberapa produk keuangan tersebut sangat kompleks dan tidak mudah dipahami terlebih untuk kaum investor yang tidak terliterasi. Masih banyak para kaum milenial yang tidak mengerti mengenai saham dan cara kerja saham dalam pasar modal meskipun mereka ingin tahu dan ingin belajar.
Dengan potret kehidupan yang demikian, seolah kaum milenial tidak mengambil keputusan investasi dengan bijak. Salah satu faktor yang menyebabkan demikian adalah literasi keuangan yang rendah (Widodo, 2015). Pada penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat kepemilikan saham terkait erat dengan literasi keuangan bukan terhadap pendidikan.
Literasi keuangan dengan level dasar (mengetahui pengetahuan sederhana dan memiliki kemampuan kalkulasi dasar) akan lebih memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pasar modal. Hubungan antara literasi keuangan dan kepemilikan saham semakin kuat dalam grup individu yang memiliki literasi keuangan yang sudah tinggi atau advanced.
Dalam survei yang dilakukan oleh FINRA (2012), menunjukkan bahwa generasi milenial terutama di Amerika memiliki tingkat literasi finansial yang lebih rendah dibanding dengan generasi sebelumnya (Mottola, 2014). Pada beberapa penelitian juga menunjukkan rendahnya literasi finansial juga terjadi pada kaum muda di berbagai negara seperti India, Lithuania dan New Zealand (Agarwalla et al., 2015 dan Cameron et al., 2015).
Di Indonesia sendiri, menurut data yang diungkapkan oleh S&P Global Financial Literacy Survey, tingkat literasi finansial pada orang dewasa hanya sekitar 32%. Sangat jauh berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura yang memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 59% ataupun Malaysia dengan tingkat literasi sedikit lebih tinggi dengan angka sebesar 36%. Sehingga, hal ini sejalan dengan data pasar modal Indonesia yang masih menunjukkan jumlah investor yang rendah di regional ASEAN.
Literasi keuangan bisa diartikan sebagai bagaimana seseorang memiliki pengetahuan dan memahami konsep tentang uang dan keuangan. Mereka juga memiliki tingkat percaya diri untuk mengimplementasikan pengetahuan terkait investasi pasar modal.
Dengan literasi keuangan yang rendah dan tanpa memahami konsep keuangan dasar, seseorang tentu tidak memiliki bekal yang cukup dalam melakukan keputusan finansial, terutama terkait pemilihan investasi. Dalam Survey Manulife Investor Sentiment Index mengatakan bahwa 60 persen dari responden ingin untuk mengontrol pengeluaran lebih baik tetapi tidak memiliki tools yang memadai dan 53 persen menyesal tidak mempersiapkan sejak dini.
Adanya inovasi keuangan berupa fintech bisa menjadi salah satu jalan atau upaya dalam edukasi produk-produk keuangan. Fintech yang telah menjadi bagian dari gaya hidup milenial akan jauh lebih mudah mengenal berbagai macam tools dalam perencanaan keuangan dan produk-produk keuangan seperti asuransi, reksa dana, ataupun saham.
Selain itu, dengan adanya produk fintech juga dapat memberikan koneksi kepada berbagai rekening bank sehingga para kaum milenial dapat melakukan pencatatan secara otomatis dan juga melakukan auto budgeting untuk memperkirakan anggaran ideal.
Salah satu produk fintech yang cukup terkenal di Amerika adalah Acorns. Acorns tidak hanya menawarkan produk investasi untuk milenial tetapi juga menawarkan bimbingan dan pendampingan. Produk Acorns dapat memaksa penggunanya untuk menabung setiap kali berbelanja dan menginvestasikan sisanya dalam rekening investasi.
Dengan seperti ini, kebiasaan konsumtif kaum milenial dapat diselaraskan dengan perilaku menabung. Jika produk fintech seperti ini dapat diterapkan di Indonesia, tentu dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.
Sumber Referensi:
Eliki Boletawa, “Financial literacy: An important tool for financial inclusion,” Alliance for Financial Inclusion, Jan. 23, 2015; http://blogs.afi-global.org/2015/01/23/financial-literacy-an-important-tool-for-financial-inclusion/IBNU HAJAR ULINNUHA, “"Fintech" dan Perilaku Keuangan Generasi Milenial”, Feb. 14, 2017; http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/14/090100326/.fintech.dan.perilaku.keuangan.generasi.milenial
Agarwalla, A. K. U., Barua, S. K., Jacob, J. and J. R. Varma (2015) Financial Literacy among Working Young in Urban India, World Development, Volume 67, Issue 8, pp. 101–109.
Kelan, E. and M. Lehnert (2009) The Millennial Generation: Generation Y and the Opportunities for a Globalised, Networked Educational System, Beyond Current Horizons, Education Department University of Bath, Bath.
Mottola, G. R. (2014) The Financial Capability of Young Adults—A Generational View, FINRA Investor Education Foundation, Washington.
Wang, Q., Chen, W., and Y. Liang (2011) The Effects of Social Media on College Students,
MBA Student Scholarship, Paper 5. http://scholarsarchive.jwu.edu/mba_student/5
Cameron, M. P., Calderwood, R., Cox, A., Lim, S., and M. Yamaoka (2014) Factors Associated with Financial Literacy among High School Students in New Zealand, International Review of Economics Education, Volume 16, Issue 2, pp. 12–21.
Oleh : M. Haris Rahmansyah
Capital Market Professional Development Program 2017
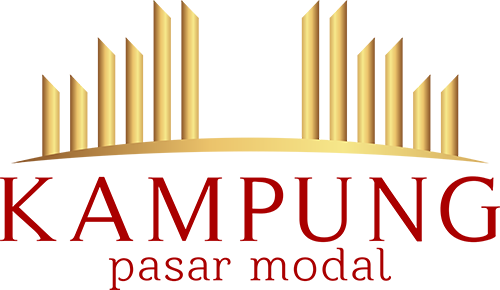

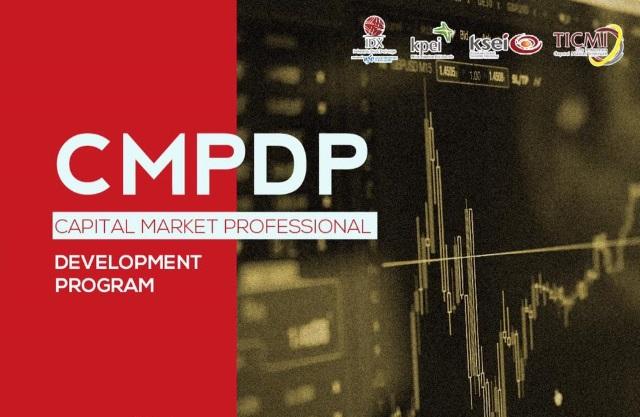
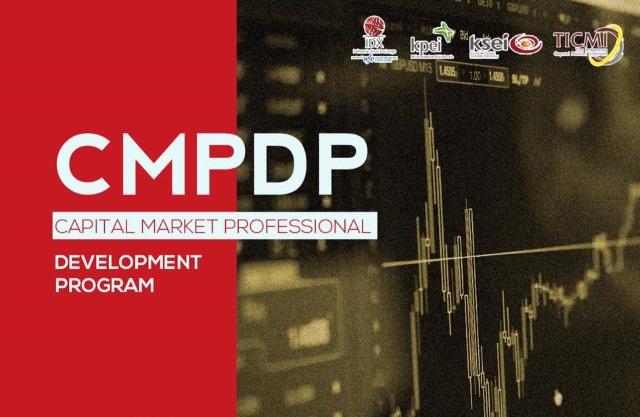
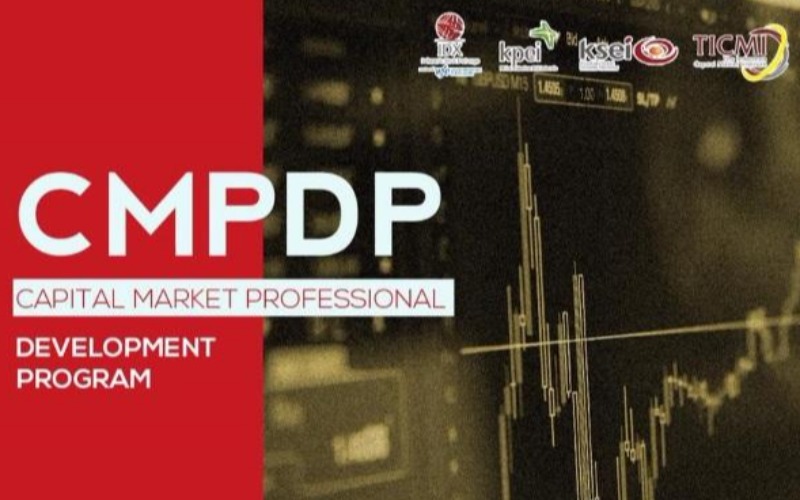
.png)