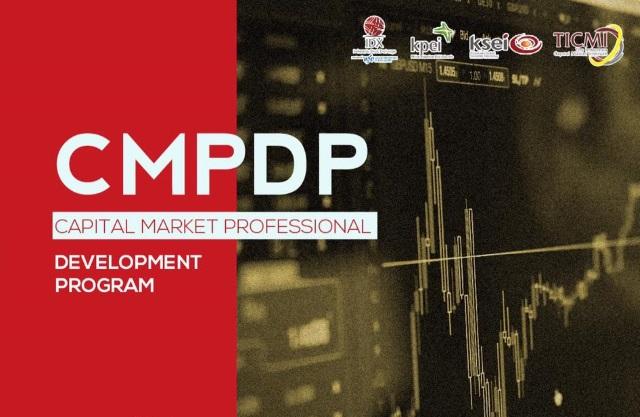Kali ini, Dream for Freedom, Cakrabuana Sukses
Indonesia dan United Nations Swissindo World Trust International Orbit menambah
panjang daftar investasi ilegal yang meresahkan masyarakat (KONTAN, 2/11).
Maraknya investasi ilegal berupa skema investasi cepat kaya (get rich quick scheme) memberi gambaran
bahwa masih ada persoalan dalam perilaku keuangan masyarakat.
Model
investasi get rich quick scheme
umumnya dilakukan dengan skema ponzi dan piramida. Skema ponzi adalah modus
investasi dimana hasil investasi yang diberikan pada investor berasal dari dana
investor lain yang baru ikut bergabung (Benson, 2009) atau tidak berasal dari
hasil aktivitas investasi yang riil sesungguhnya (Lewis, 2012). Skema piramida
hampir sama dengan skema ponzi. Namun dalam skema piramida, investor harus mengajak
investor baru untuk bergabung seperti dilakukan melalui arisan berantai.
Di
Indonesia, model penawaran investasi dengan skema ini lebih dikenal dengan
istilah investasi bodong. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan investasi
bodong mulai beroperasi di Indonesia, KONTAN mencatat modus investasi ini sudah
memakan korban sejak 1975. Adakah sesuatu yang salah sehingga modus investasi
ini kembali terus terulang ?
Bias perilaku
Shiller
(2000) menyatakan bahwa skema ponzi adalah bentuk irrational exuberance dan menggambarkan perilaku psikologis dimana
orang bertindak tidak rasional. Greenspan (2008) juga menyatakan bahwa
pendekatan psikologis dapat memberikan jawaban dalam memahami alasan seseorang
terlibat skema ini. Pendekatan psikologi dalam ilmu keuangan sepertinya tepat
dalam persoalan ini dikarenakan memiliki asumsi bahwa manusia adalah makhluk
yang tidak selalu rasional dalam mengambil keputusan.
Dalam
perspektif ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional yang selalu berusaha
memaksimalkan keuntungan. Tapi manusia tidak selalu rasional karena ada
pengaruh psikologis yang diwujudkan dalam bias perilaku. Faktor psikologis itu
mempengaruhi seseorang untuk berinvestasi dalam skema ponzi dan piramida (Elan,
2010; Lewis, 2012).
Beberapa
bias perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pada skema ini adalah
optimism bias, overconfidence, representativeness
bias, confirmation bias, framing dan herding. Optimism bias
adalah kecenderungan seseorang untuk melebih-lebihkan kemungkinan bahwa hal-hal
yang baik akan terjadi dan meremehkan potensi peristiwa yang tidak
menyenangkan. Ia optimistis skema itu benar dan akan mengalami hal yang sama
seperti investor lain yang sudah mendapatkan keuntungan.
Individu
yang mengalami optimism bias lebih
percaya diri (overconfidence) karena
merasa memiliki kelebihan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dibanding
orang lain. Riset Camerer dan Lovallo (1999) membuktikan bahwa individu yang overconfidence cenderung menyukai
aktivitas berisiko. Dan benar terbukti overconfidence
adalah salah satu faktor yang membuat investor menjadi korban penipuan
investasi seperti pada skema ponzi (Elan, 2010) dikarenakan keyakinan bahwa
mereka tidak akan menjadi korban penipuan (Kaul, 2013).
Faktor
lain yaitu representativeness bias
ketika seseorang tertarik dengan suatu skema karena keberadaan seseorang atau
sekelompok orang yang disegani atau dikagumi dalam skema ini. Keberadaan mereka
terkadang memang sengaja digunakan sebagai stereotype
untuk menarik perhatian investor baru. Skema ini sering memanfaatkan kehadiran
orang tertentu di sebuah komunitas untuk mencari investor baru (Reurink, 2016).
Seringkali mereka public figure yang memiliki reputasi di
masyarakat dan menjadi magnet bagi investor.
Korban
skema investasi ponzi yang dilakukan Bernard Madoff juga salah satu contoh
adanya representativeness bias (Yong,
2013). Madoff mampu menarik banyak investor karena ia penganut Yahudi taat di
komunitasnya dan disegani di kalangan investor Wall Street. Di Indonesia, skema
yang ada seringkali memanfaatkan pejabat, artis, tokoh agama dan tokoh
masyarakat untuk menarik investor seperti dilakukan pengelola Qurnia Subur Alam
Raya, Golden Traders Indonesia Syariah dan Raihan Jewellery.
Keberadaan
skema ini sulit dibedakan dengan investasi legal manakala skema ini ikut
mendukung kegiatan resmi sehingga investor merasa skema itu adalah legal dan
aman. Sebagai contoh, MMM dari Rusia ikut mensponsori tim sepak bola Rusia pada
piala dunia 1994.
Selain
stereotype, representativeness bias menurut M. M. Pompian (2006) juga bisa
berarti investor menggunakan “the law of
small numbers” yaitu menganggap sampel kecil merupakan gambaran sebenarnya
dari populasi. Beberapa orang yang sudah mendapatkan pengembalian dari suatu
skema investasi akan dianggap mewakili kondisi yang akan dialami oleh seluruh
investor.
Representativeness bias kemudian dapat memunculkan confirmation bias, yaitu kecenderungan
seseorang mencari informasi yang mendukung pendapatnya atau mengesampingkan
informasi yang tidak mendukung pendapatnya. Confirmation
bias dalam skema ini terlihat ketika investor mengabaikan peringatan terhadap
skema investasi itu (Shefrin, 2015).
Keinginan
seseorang melakukan investasi semakin kuat ketika terjadi framing, yaitu kecenderungan mengambil keputusan berdasarkan
informasi yang disajikan. Pengelola skema umumnya membingkai informasi dengan
frame positif, yaitu memberikan informasi yang baik kepada calon investor,
misalnya keberhasilan orang yang sudah dapat keuntungan.
Bias
perilaku lain adalah herding, yaitu
seseorang yang mengikuti orang lain atau meniru perilaku kelompok dalam
mengambil keputusan daripada memutuskan sendiri. Banyaknya orang di lingkungan
sekitar yang ikut investasi ilegal membuat seseorang tertarik bergabung karena
ia juga ingin jadi bagian dari orang-orang yang ‘sukses’.
Bagi mereka yang menjadi korban akibat ketidaktahuan, program literasi keuangan adalah salah satu solusi menyelesaikan persoalan. Problem utamanya justru ada pada investor yang sebenarnya mengetahui mekanisme fraud yang dilakukan pengelola. Riset Stephenson (2014) dan Hidajat (2016) menunjukkan korban investasi ilegal justru memiliki skor literasi keuangan lebih tinggi dibanding mereka yang bukan korban. Literate namun irasional. Inilah yang membuat investasi ilegal sulit ditangkal dan kembali terus terulang.
By : Taofik Hidajat
Dosen STIE Bank BPD Jateng; Sedang Menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Padjajaran
Artikel ini telah terbit
sebelumnya pada Senin, 07 November 2016 di https://m.kontan.co.id/news_analisis/irasionalitas-dalam-investasi?page=2
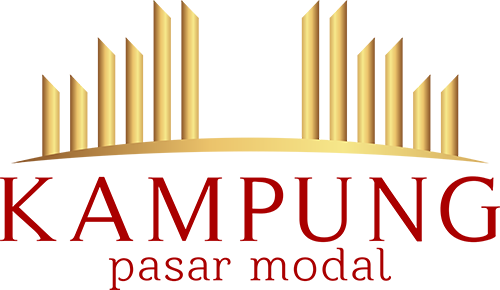



.png)